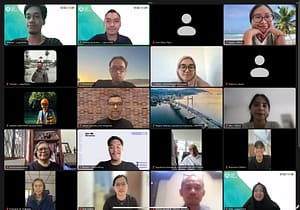Oleh ALFIATUL KHAIRIYAH*
MASYARAKAT Madura pelan-pelan meninggalkan lahan pertanian jika kondisi iklim semakin memburuk dan tak ada tindakan apa pun dari pemerintah untuk memulihkan aktivitas pertanian. Hal ini akan membuat banyak lahan tidak produktif, masyarakat meninggalkan Pulau Madura, hingga terancamnya ketahanan pangan dan sistem mata pencaharian berkelanjutan.
Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini telah mengubah beberapa aspek sosial, mulai dari mata pencaharian, pola hidup dalam pertanian, dan lainnya. Bagi masyarakat agraris, iklim adalah kunci menjalankan kerja-kerja produksi pertanian. Madura, wilayah dengan mayoritas penduduknya sebagai petani, juga merasakan dampak dari kondisi iklim akhir-akhir ini.
Kemarau panjang dan surplus air di waktu-waktu tertentu telah menyebabkan kondisi pertanian tidak menentu. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021–2026, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan selama 2019–2020. Di Kabupaten Pamekasan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di sektor pertanian juga berkurang sejak 2012–2017. Sedangkan pertumbuhan di sektor lain semakin meningkat seperti sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan penyediaan akomodasi. Hal ini terjadi beriringan dengan perubahan iklim.
Fenomena Krisis Iklim di Madura
Madura sebagai wilayah yang kering dan curah hujan yang minim, sangat terdampak pada krisis iklim berupa fenomena kekeringan. Suhu Madura juga cukup tinggi. Badan Meteorologi dan Klimatologi pada laporan 2006 mengatakan, suhu Madura berkisar antara 27o–30o. Hari ini suhu tersebut bisa mencapai 36o. Seperti yang terjadi di Sampang, dilansir dari RRI Sampang, suhu pada Oktober 2023 mencapai 36.2o.
Madura mengalami surplus air selama 5 bulan saja. Sisanya, Madura mengalami defisit air. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi di beberapa wilayah pada musim kemarau terakhir, banyak kabupaten di Madura menyalurkan air ke desa-desa yang mengalami kekeringan panjang. Data liputan Walhi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada 2024 sebanyak 27 kabupaten di Jawa Timur mengalami kekeringan. Di antaranya kabupaten di Madura seperti Sampang dengan 102 desa dan Kabupaten Pamekasan dengan 72 desa.
Yang perlu diketahui bahwa krisis iklim bukanlah fenomena yang tiba-tiba turun dari langit. Namun, ia adalah hasil dari aktivitas-aktivitas manusia yang cenderung destruktif terhadap lingkungan seperti deforestasi, efek gas rumah kaca (GRK), dan industrialisasi. Berdasarkan data badan pusat statistik, angka deforestasi di Provinsi Jawa Timur di tahun 2014 mencapai 7.497,1 ha. Di antaranya, demi kepentingan industri.
Migrasi Madura dan Pertanian
Krisis iklim yang menyebabkan kekeringan telah mengubah proses pertanian di Madura. Salah satunya adalah kalender tanam seperti waktu tanam dan waktu panen sulit ditentukan karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Tidak hanya itu, kekeringan panjang ini juga sering kali membuat petani merugi akibat terancamnya gagal panen dan masa tanam yang tidak sesuai kebutuhan.
Masa tanam padi yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu musim sekitar 5 tahun terakhir tidak dapat diberlakukan di seluruh wilayah Madura secara merata. Beberapa wilayah hanya bisa melakukan tanam padi satu kali selama musim hujan. Hal ini terjadi di Kabupaten Pamekasan. Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) pada awal Februari mengatakan bahwa petani yang dapat melakukan dua kali penanaman selama satu tahun hanya area sawah yang dekat dengan irigasi. Sementara kondisi irigasi di pedesaan juga tidak cukup baik.
Perubahan kalender tanam dan ancaman gagal panen di setiap musim direspons oleh masyarakat Madura dengan berbagai alternatif untuk tetap menyambung hidup. Yakni, menggeser mata pencaharian masyarakat dari petani ke perdagangan. Beralihnya mata pencaharian demi penyesuaian pekerjaan akibat krisis iklim dapat dilihat dari menjamurnya toko kelontong yang kita sebut ”warung Madura”. Masyarakat, khususnya petani, cenderung memilih menjaga warung Madura di luar pulau dan ke kota-kota besar seperti di Surabaya dan Jakarta serta kota kota satelit lainnya.
Perubahan sosial ekonomi, migrasi sementara yang dilakukan masyarakat Madura untuk menjaga warung, dan mata pencaharian yang berubah juga sejalan dengan fungsi lahan yang semakin hari berubah menjadi wilayah pembangunan perdagangan. Proses ini telah sejalan dengan deagrarianisasi. ”Warung Madura” menjadi kekuatan yang menonjol bagi perubahan ekonomi dan sosial sejak beberapa tahun terakhir. Bersamaan dengan menurunnya produktivitas pertanian karena krisis iklim dan regulasi harga.

Deagrarianisasi hingga Reagrarianisasi
Peralihan orientasi masyarakat agraris dari sektor pertanian menuju sektor nonagraris seperti industri dan perdagangan merupakan salah satu indikator dari proses deagrarianisasi. Bryceson (2018) telah menuliskan persoalan deagrarianisasi yang terjadi di Afrika dengan beberapa indikator. Di antaranya, reorientasi mata pencaharian, penyesuaian pekerjaan, penataan ulang spasial permukiman tempat tinggal, dan identifikasi ulang sosial yang menjauh dari pola agraris.
Beberapa indikator tersebut juga terjadi di Madura. Berpindahnya mata pencaharian dari pertanian ke perdagangan sebagai respons masyarakat di tengah krisis iklim. Sementara, harapan terhadap perbaikan kondisi lingkungan juga pupus. Bersamaan dengan berkurangnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, rencana pembangunan malah mendorong transformasi ekonomi pada industri kreatif, koperasi, industri kecil, dan lainnya dibandingkan pertanian itu sendiri. Hal ini tertulis di RPJMD Kabupaten Sumenep.
Deagrarianisasi ini tentu menjadi problem yang perlu disorot karena pertanian sebagai sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Madura. Selama ini, penunjang ekonomi terbesar Madura adalah sektor pertanian. Di Pamekasan, pertanian menunjang 39 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan di Bangkalan menyumbang 35.61 persen terhadap PDRB.
Selain itu, sumber daya alam berupa lahan yang ditinggalkan oleh masyarakat memungkinkan munculnya industri-industri ekstraktif baru di Madura seiring dengan terbukanya akses Jembatan Suramadu. Hal ini sudah terjadi, industri pertambangan yang bermunculan mulai menggeser kepemilikan lahan warga menjadi milik orang luar. Deagrarianisasi yang terjadi di Madura tidak hanya mengancam pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Madura. Tetapi, juga mengancam kedaulatan lahan masyarakat Madura dan terlaksananya pembangunan berkelanjutan di Madura.
Deagrarianisasi di Madura perlu dihentikan. Transformasi ekonomi ramah lingkungan dan pemulihan iklim perlu dilakukan untuk mengembalikan lahan-lahan produktif. Hal ini demi ketahanan pangan berkelanjutan, khususnya di wilayah Madura, dan mempertahankan kedaulatan sumber daya alam serta menjaganya dari industri ekstraktif yang justru merusak Madura dari luar. Pemerintah dapat memulai dengan reagrarianisasi yang didukung oleh berbagai kebijakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura yang mayoritas bekerja sebagai petani. (*)
*)Researcher di Academic and Social Studies (ACCESS)
Artikel ini dirilis juga di: https://radarmadura.jawapos.com/opini/745845852/deagrarianisasi-dan-perubahan-iklim-madura?page=2